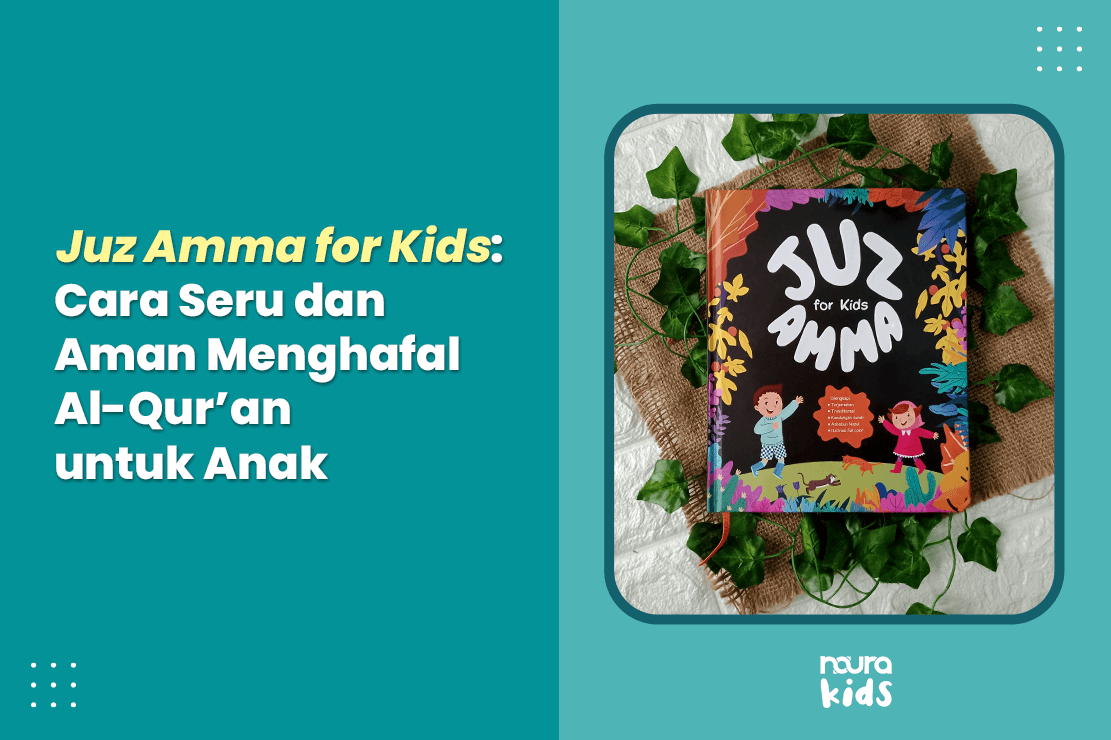Bagi penganut paham kreasionisme jagat ini diciptakan oleh Tuhan. Melalui kandungan “Rahman” dan “Rahim” Tuhan terlahirlah cinta. Ia menjadi bekal utama seluruh makhluk untuk menjalankan proses hidup dan kehidupan. Membaca pola demikian, kita segera memahami muatan semantik (makna) kandungan puisi Cak Nun yang kemudian dipakai sebagai judul utama antologi ini.
Puisi Rahman Rahim Cinta bagian pertama dan kedua (hlm. 58-59) merupakan sajak yang menggambarkan peristiwa penciptaan alam semesta. Cinta dihadirkan bukan hanya sebagai makna hubungan antarindividu, melainkan “ikon utama kepribadian-Nya” yang meluas dan mendalam. Apa pun pengertian cinta, sebagaimana ditafsirkan orang selama ini, tetap tak mampu merengkuh hakikat di baliknya. Cinta bisa sangat akrab tapi sekaligus begitu abstrak.
Cinta bukan kata yang kau pungut suatu siang dari tepian jalan
Dari puisi penyair yang tertulis di sobekan kertas koran
Cinta bukan rerasanan yang tercantum di footnote kaum ilmuan
Atau dari surat cinta seorang pemuda kepada perawan
Lantas kau ambil, kau bawa pulang dan kau jadikan hiasan
Bahkan kau jadikan komoditas untuk meraih kepentingan
Sabrang Mowo Damar Panuluh (SMDP) pernah membagi tiga tingkatan cinta. Level pertama cinta adalah cinta seorang anak kepada barang kesayangannya. Ia mencintai barang itu hingga tak boleh disentuh atau dimiliki orang lain. Cinta semacam ini lebih individual. Lapisan berikutnya adalah cinta seorang remaja kepada sang kekasih. Ia sebetulnya sekadar mencintai diri sendiri melalui pantulan orang lain. Tingkatan paling atas adalah cinta tanpa prasyarat, seperti cinta seorang ibu kepada anaknya.
Baca juga: Dongeng Kemoceng dan Catatan Untuk Diriku
Pembabakan itu nyaris seperti penggalan sajak di atas. Cinta yang “serba bukan” kecuali yang sejati. Sementara kesejatian, sebagaimana kita pahami dalam sajak-sajak Cak Nun, selalu berasal, melalui, dan termiliki oleh Tuhan. Manusia hanya mendapatkan cipratan-cipratan itu. Tak mengherankan bila pemahaman akan cinta hasil pergumulan manusia sangat mungkin membuat “rekayasa” atau “salah paham” seperti penggalan pertama Rahman Rahim Cinta (2) berikut.
Tolong jangan main-mainkan cinta menjadi camilan kesenian
Atau kau rekayasa menjadi slogan politik dan kebudayaan
Kemudian dalam agama jadi mazhab saling salah paham
Ketiga baris di atas mencitrakan kritik sosial penyair. Meskipun kata cinta tak terucapkan langsung oleh politikus atau budayawan, tapi terlihat bahwa mereka acap merekayasa kata ini sebagai sebuah slogan, jargon, bahkan barangkali propaganda. Kecenderungan ini menegaskan cinta dalam pengertian sempit, sektoral, atau provinsional. Cinta demikian, bila terejawantah dalam agama, menyembul dalam bentuk mazhab.
Sudah banyak upaya “rekayasa cinta” yang dilakukan pemeluk agama. Mereka merasa itu cinta dari agama. Padahal, seseungguhnya itu merupakan kungkungan mazhab. Apakah mazhab berarti mengungkung cinta ke dalam tempurung kesempitan, membelenggu keluasan sekaligus kedalaman yang sebelumnya menjadi kekhasan rahman dan rahim?
***
Garis besar puisi-puisi di antologi ini masih satu langgam dengan karya Cak Nun yang sebelumnya kita kenal dalam Sesobek Buku Harian Indonesia (1993) atau 99 untuk Tuhanku (1983). Cak Nun lebih memilih gaya kepenulisan liris, tidak keluar, tapi ke dalam diri sendiri. Bila puisi-puisi sebelumnya lebih dominan memakai rima bebas, di antologi ini tampaknya agak berbeda. Ia sering memakai akhiran /a/, /n/, atau /m/. Perhatikan akhiran dua penggalan puisi di atas.
Pemilihan rima semacam ini setidaknya mempunyai tiga tampilan. Pertama, rima sebagai tekanan pada tiap larik atau akhir puisi. Kedua, rima sebagai upaya untuk memberikan nada tinggi. Misalnya penekanan pada kata “serampangan” atau “salah paham”. Ketiga, rima sebagai bentuk perpanjangan suara dari baris sebelumnya. Namun, rima dalam puisi-puisi Cak Nun cenderung masuk ke dalam tampilan kedua.
Baca juga: Belajar Kemanusiaan dan Keberagamaan dari Buku Habib Ali al-Jufri
Bagian puisi lain, sejauh kita baca di sini, lebih memakai rima aliterasi atau pengulangan bunyi konsonan. Sebagai contoh puisi berjudul Kebun (hlm. 63). //Karena Tuhan tidak menunjukkan sertifikat//Oleh manusia kini tanah disekat-sekat//Hak asasi Tuhan telah dijebrat. Bukankah dominan penggunaan “at” di dalamnya?
Terlepas dari kecenderungan gaya puisi Cak Nun, antologi ini meneruskan “catatan-catatan kesaksian”—pinjam istilah Suminto A. Sayuti—yang sudah dimulai dari karya-karya sebelumnya seperti yang telah disinggung di awal. Sebagaimana sebuah kesaksian, ia ditulis seperti “buku harian” yang mewedarkan perubahan sosial yang diamati penyair di sekitarnya. Kendati demikian, Cak Nun konsisten memakai teknik ekspresi yang bersahaja sehingga mudah dipahami pembaca luas.
Bagi Cak Nun, menulis puisi seperti halnya menulis esai atau naskah drama, tidak berpretensi puitik atau literer tapi langsung menghidangkan “substansi” pembahasan tanpa teding aling-aling. Seperti diakuinya di dalam antologi, “Maka puisi ini tak kumaksudkan sebagai khazanah sastra. Sekadar supaya anak cucuku mengingatnya. Bahwa orangtuanya benar-benar menjadi manusia.”
Pada usia ketika jamak generasi muda sudah memanggilnya sebagai Mbah, upaya penerbitan antologi puisi memang mengingatkan kita agar terus merawat kehidupan melalui puisi. Tanpa puisi, menurut Cak Nun, “… negara, kebudayaan, dan agama: kehilangan manusia” (hlm.282). Seperti diungkap di pembukaan, kreasionisme atas semesta adalah tindakan puitis yang berasal dari rahman dan rahim. Sedangkan Cak Nun, lewat karya kreatifnya, mengetuk pintu nurani kita agar senantiasa mengingat bahwa kehidupan berawal dan berlangsung dalam proses memuisi.
Ketukan itu terlihat bernas saat kita membaca empat puisi antara lain “Padang Bulan” (hlm. 237), “Kenduri Cinta (hlm. 239), “Bangbang Wetan” (hlm. 241), dan “Mafâzâ” (hlm. 243). Boleh jadi ia ditulis khusus untuk simpul Maiyah tertentu. Boleh jadi pula ada pesan simbolik di dalamnya yang dialamatkan kepada penggiat. Namun, tentu saja, meski ditulis spesifik, puisi-puisi itu terbuka bagi pesan-pesan universal di satu pihak tapi akan mempartikular di pihak lain. Sekali lagi, semua tafsir, bergantung kepada kita: sang pemberi makna.
Kesatuan tematis apa yang menyatukan seluruh puisi di sini? Pada puisi Kenduri Cinta kita segera mendapatkan jawaban.
Cinta bagai Tuhan itu sendiri
Tunggal tapi bersemayam di semuanya