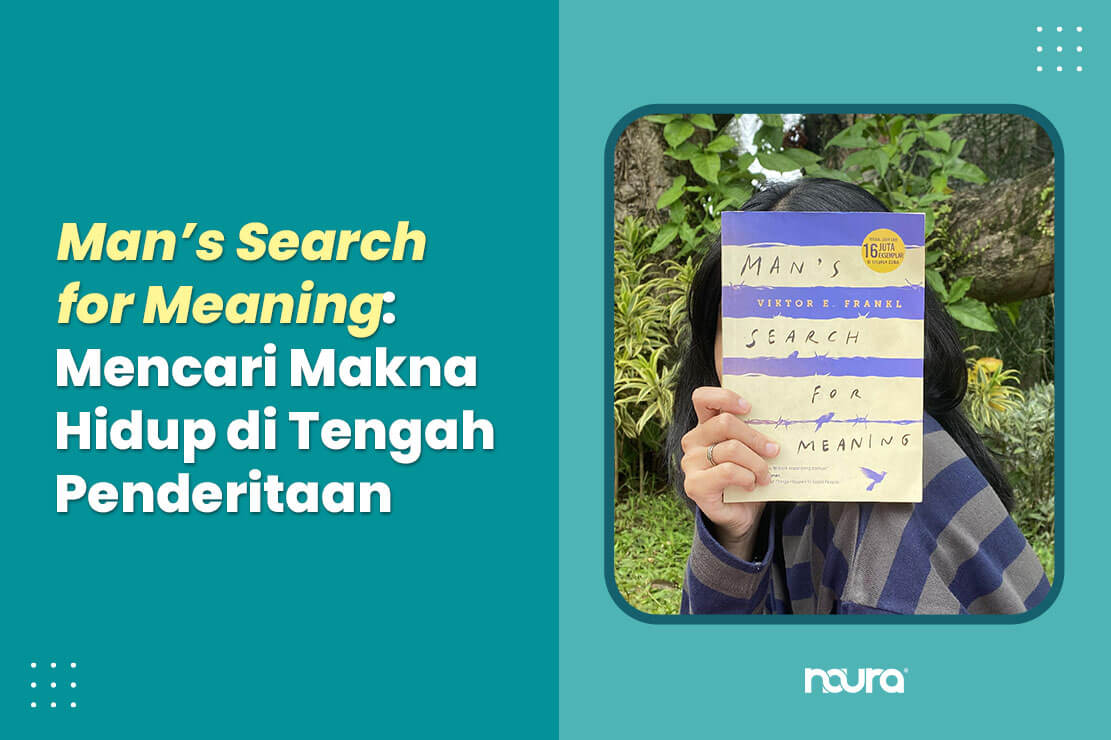Kurangnya perhatian terhadap penulisan sejarah peran golongan Islam dalam perjuangan di era Revolusi Indonesia mendorong Kevin W. Fogg, peneliti asal Amerika Serikat, untuk menuliskan seluk-beluk perjuangan mereka di era tersebut. Bukunya yang berjudul Indonesia’s Islamic Revolution telah terbit pada tahun 2019, dan versi bahasa Indonesianya, Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia, akan diterbitkan dalam waktu dekat. Simak obrolan dengan Kevin seputar isi bukunya dan cerita di balik penulisan bukunya tersebut.
“Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu umat Islam yang mati dalam peperangan itu syahid.” Perkataan tersebut terlontar dari mulut KH. Hasyim Asy’ari dalam cuplikan adegan film Sang Kiai yang dirilis pada tahun 2013. Dalam cuplikan adegan tersebut digambarkan para kyai berkumpul di markas GP Ansor di Surabaya pada Oktober 1945 dalam rangka menghasilkan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad ini yang kemudian menjadi pijakan bagi golongan Islam untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Cuplikan adegan tersebut memang belum tentu akurat secara sejarah. Akan tetapi, cuplikan adegan tersebut tentu membawa pesan: golongan Islam turut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hanya saja menurut Kevin W. Fogg, mayoritas narasi sejarah Revolusi Indonesia masih negara-sentris, yang lebih menonjolkan peran alat-alat negara. Sedangkan peran akar rumput golongan Islam masih belum mendapat tempat yang layak.
“Jadi lebih banyak fokus ke TNI dan perang mereka untuk memerdekakan Indonesia. Ada juga (narasi) yang menguntungkan instansi-instansi negara saat itu,” kata Kevin dalam diskusi daring “Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia” yang diselenggarakan penerbit Noura Publishing pada (10/11/2020).
“Ada yang terlupakan atau dikesampingkan, yaitu spirit yang muncul dari akar rumput, bagaimana mereka di semua daerah di Indonesia turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” tambahnya.
Dalam bukunya Kevin menulis peran penting Islam sebagai ideologi revolusioner yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Golongan Islam turut berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia demi tujuan-tujuan yang suci. Ini berbeda dengan penulisan sejarah Revolusi Indonesia yang selama ini didominasi perjuangan nasionalistik ataupun berbasis kelas.
“Saya mendalami di akar rumput komunitas santri atau Islam yang taat, bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apakah itu berbasis Islam atau apakah itu ada dampak bagi agamanya, bagaimana mereka membentuk laskar atau dapur umum, atau bagaimana mereka memperjuangkannya dengan bentuk-bentuk Islami,” ujarnya menambahkan.
Alasan Kevin lainnya menulis sejarah Revolusi Indonesia dari kacamata golongan Islam adalah, “Karena mereka yang terbanyak jumlahnya saat itu tapi saya juga rasa sumbangannya ke revolusi tidak bisa dilupakan, sangat penting bagi hasil-hasil revolusi seperti kita lihat masa-masa sekarang.”
Lebih lanjut, Kevin menyebut jika sebenarnya pada masa revolusi, perjuangan mayoritas masyarakat Indonesia tidak terkait dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun alat-alat negara yang lain. Dengan kata lain, perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersifat mandiri, tanpa campur tangan negara.
“Banyak dari mereka yang mengikuti laskar atau perjuangan yang sangat lokal, yang tidak ada kaitan eksplisit atau hubungan komunikasi dengan (pemerintah) pusat,” ujarnya.
Meskipun mengangkat sejarah perjuangan golongan Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan berarti kemudian golongan Islam menjadi satu-satunya golongan yang turut aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Itu (golongan Islam) hanya satu dari beberapa perspektif yang lain. Ada juga yang cenderung kiri, nasionalis sekuler, ada juga yang (hanya) ingin meperjuangkan daerahnya. Saya fokus pada golongan Islam, karena itu salah satu yang ditulis tidak dengan perhatian yang layak,” ujar Kevin.
Kekuatan Supranatural
Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di era revolusi, laskar-laskar Islam dikenal golongan yang nekat dalam menyerang musuh. Ini dikarenakan mereka percaya kekuatan supranatural dapat membantu mereka di medan peperangan
“Mereka pakai jimat, mantra, yang umumnya magis, tapi dengan nuansa Islami. Magis itu karena diciptakan oleh haji, kyai, atau yang dianggap alim. Mereka mempercayai itu akan melindungi atau memperkokoh mereka dan membawa kemenangan kepada mereka,” kata Kevin.
Kevin mencontohkan kegilaan para pejuang dari laskar Islam dalam Pertempuran 10 November di Surabaya. Mereka berada di garis terdepan dalam menyerang Inggris. Namun karena terlalu percaya pada kekuatan supranatural tersebut, banyak korban berjatuhan dari pejuang laskar Islam.
“Banyak mereka yang tidak survive karena terlalu percaya jimatnya (padahal) tidak seefektif yang mereka harap,” ujarnya.
Resolusi Jihad
Salah satu momen penting dalam perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ialah fatwa dari para ulama. Paling terkenal tentu saja ialah Resolusi Jihad yang dikeluarkan para kyai yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), meskipun di berbagai daerah juga muncul fatwa yang mewajibkan umat Islam setempat ikut berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Sebenarnya pada zaman itu banyak fatwa yang muncul dari mana-mana. Dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Lombok. Tidak hanya di Jawa yang mewajibkan orang Muslim ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang menolak kembalinya tentara Belanda, dan ikut mendukung berdirinya pemerintahan Republik Indonesia,” kata Kevin.
Munculnya fatwa-fatwa lokal yang menyerukan umat Islam untuk berjihad tidak terlepas dari kondisi komunikasi di masa itu yang sulit. Sehingga banyak fatwa seruan berjihad yang muncul di masing-masing daerah, meskipun di daerah lain telah terbit fatwa serupa.
“Seperti contoh di Medan ada Jamiatul Washliyah yang juga menerbitkan ulang fatwa yang pernah dikeluarkan di Bukittinggi, Jakarta, Jawa Timur,” ujar Kevin.
Karena saat itu masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf, maka fatwa disebarluaskan melalui khutbah salat Jumat. Fatwa disebarluaskan dalam bentuk tulisan agar bisa dibacakan para khatib
“80 persen masyarakat Indonesia buta huruf pada tahun 1950. Jadi kebanyakan dengar fatwa ini sebagai bagian dari khutbah Jumat, jadi itu disampaikan saat Jumatan karena itu kesempatan untuk mengumpulkan banyak orang supaya mereka dengar perintah yang sama,” ujar Kevin.
Kesenjangan Elit dan Akar Rumput
Meskipun perjuangan dalam revolusi didorong oleh ideologi yang sama, tapi terdapat perbedaan pandangan dalam golongan Islam antara kelompok akar rumput dan elit. Pengaruh pendidikan Barat membentuk pola pikir elit yang lebih mengutamakan perjuangan diplomasi dibanding angkat senjata.
“Orang seperti Natsir, Jusuf Wibisono, Sjafrudin Prawiranegara, Mohammad Roem… pemahaman mereka mengenai pemerintahan, agama, dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan akar rumput… Mereka maunya sangat rasionalis, maunya dianggap modern, maunya diakui negara-negara lain, tidak hanya diakui rakyat Indonesia, tapi juga diakui pemerintah yang ada di Washington, London, Tokyo, Prancis,” tutur Kevin.
Kalangan elit yang lebih rasional juga skeptis terhadap kekuatan supranatural yang dipercayai oleh kalangan akar rumput. “Mereka tidak percaya pada mantra atau jimat. Malah ada yang di antara mereka, Sjafruddin atau Mohammad Roem, yang ketawain orang yang pakai jimat,” ujar Kevin.
Kevin menyebut jika pandangan skeptis terhadap kekuatan supranatural tidak hanya dari kelompok tradisionalis. Kalangan akar rumput kelompok Islam modernis pun ada yang memercayai kekuatan supranatural.
“Muhammadiyah atau modernis, mereka juga ada jimat di kalangan akar rumput. Jadi tidak hanya NU atau tradisionalis,” ujarnya.
Tantangan Penulisan Buku
Selain berbicara soal isi buku, Kevin juga membahas cerita di balik penulisan buku. Buku itu sendiri merupakan hasil dari disertasi doktoral di Yale University yang kemudian ia tulis ulang.
“Disertasi saya tidak hanya merangkap sejarah Revolusi Indonesia, tapi juga sejarah politik Islam Indonesia sampai dasawarsa 60-an. Belakangan saya hanya ambil bagian pertamanya saja, khususnya bagian revolusi untuk diterbitkan sebagai buku,” katanya.
Ia pun membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk menerbitkan tulisan disertasinya menjadi buku. Tantangan terberat yang dihadapinya ialah lambannya perizinan penelitian di Indonesia bagi peneliti asing.
“Itu makan waktu beberapa bulan untuk melaporkan diri di Kemristekdikti untuk dapat semua surat-suratnya,” ujar Kevin.
Tantangan lain yang ia hadapi ialah arsip-arsip peristiwa di era revolusi yang tersimpan di Arsip Nasional atau Arsip Daerah lebih banyak terkait dengan alat-alat negara ataupun ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, ia harus turun langsung mencari dan mewawancarai narasumber yang terkait langsung dengan peristiwa di era revolusi.
“Pengalaman di akar rumput memang tidak tersimpan di Arsip (Nasional atau Daerah), jadi harus turun lapangan untuk cari narasumber yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia waktu itu,” katanya.
Narasumber yang ia temui pun ada yang ingatannya sudah tidak tajam karena faktor umur. Ini terjadi pada salah satu narasumber seorang kiai sepuh di Sulawesi Selatan yang ia wawancarai.
“Umurnya sudah 102 (tahun), ingatannya tidak setajam saat seperti sebelumnya, jadi kadang-kadang cerita harus dimulai ulang atau diperiksa ulang karena tidak nyambung dari cerita pertama,” ujar Kevin. (fja)