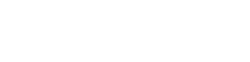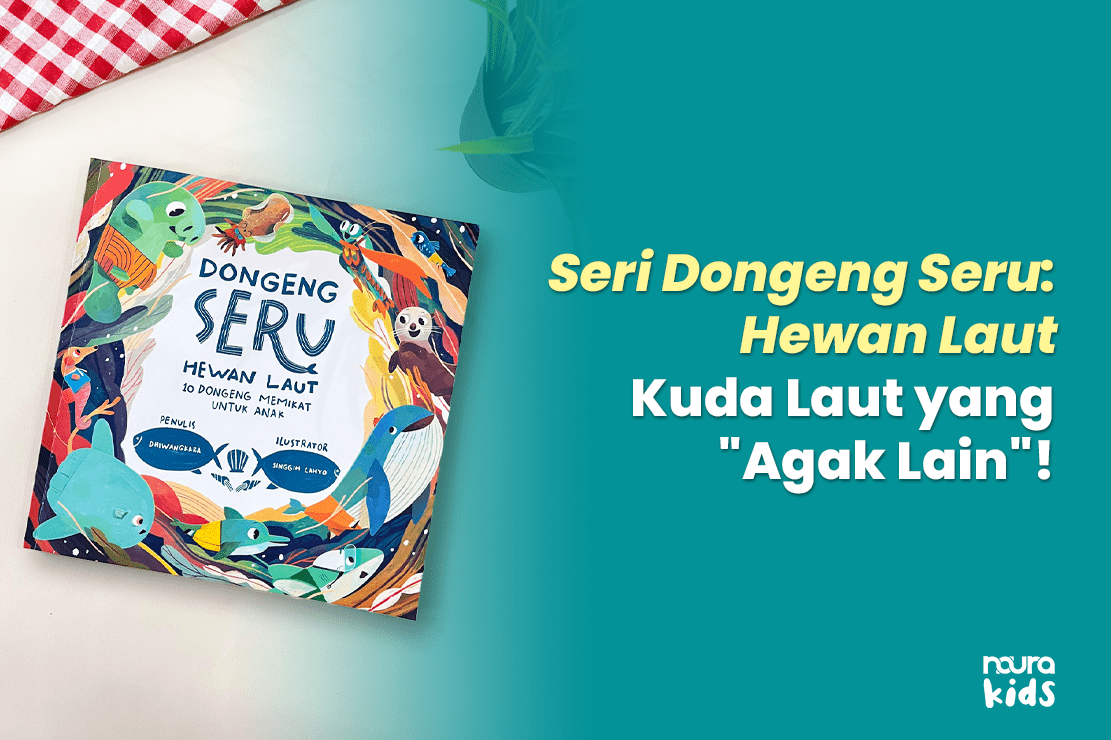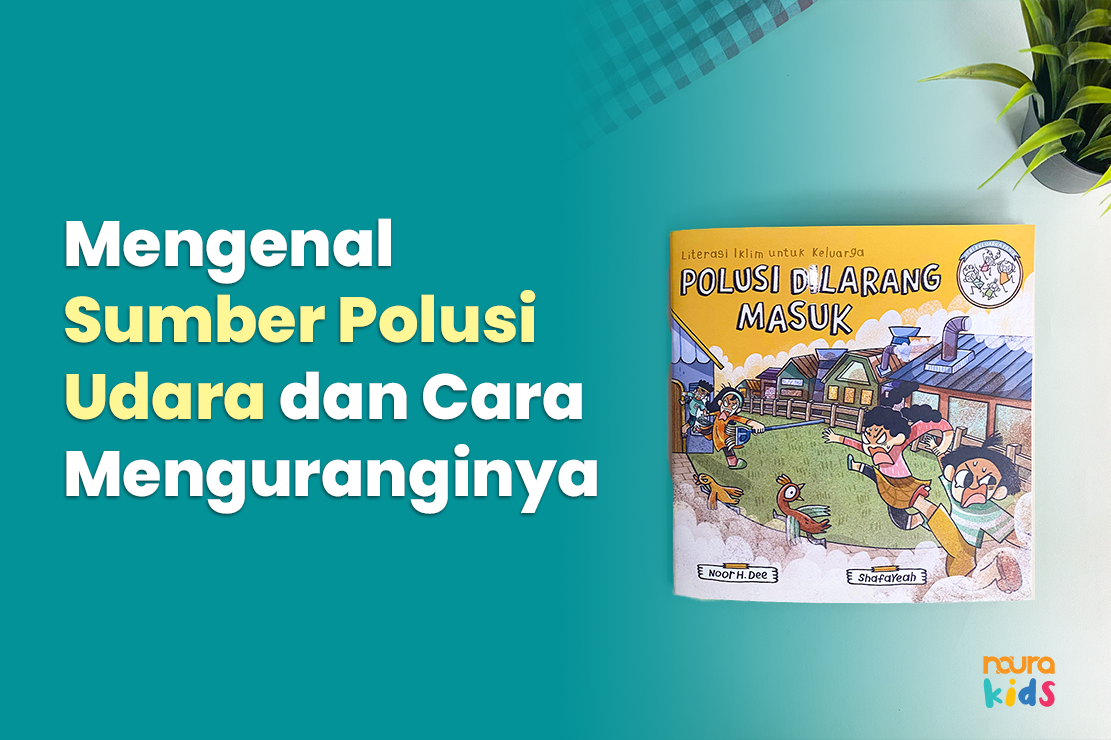Saya Haidar Bagir Alhabsyi. Tetapi, saya tak pernah memakai nama marga saya itu—Alhabsyi—di belakang nama saya. Dan jika ingatan saya benar, saya dengan penuh kesadaran melakukan hal itu. Kesadaran apa itu? Karena saya tak ingin diidentifikasi sebagai “Arab” dan lebih senang dianggap sebagai bangsa Indonesia seperti yang lain (sayang sekali wajah saya: alis, mata, hidung, sama sekali tak menggambarkan keindonesiaan. Apa boleh buat, wong sudah dari sononya begitu …).
Dan ternyata bukan hanya saya. Kami delapan bersaudara tak ada satu pun yang menempelkan nama marga di belakang nama kami. Dan ayah kami pun, Muhammad Bagir Alhabsyi, bukan saja tak berkeberatan, tetapi justru mendukung sikap dan keputusan kami. Ayah kami, yang lahir dari seorang ayah migran asli kelahiran Provinsi Hadhramaut, Yaman (Selatan), memang menunjukkan preferensi yang sama. Meski beliau seorang ustaz yang sering didaulat untuk berceramah agama, beliau memilih untuk selalu memakai sarung, kemeja (tak jarang dibalut jas), dan songkok hitam khas Nusantara.
Banyak orang menyukai ceramah beliau yang progresif, cenderung rasional, tetapi mudah dipahami. Sebagian besar audiensnya adalah sesama orang keturunan Yaman di Solo. Mereka memuji-muji ilmu beliau. Kalaupun ada kritik kepada beliau, maka itu lebih terkait soal pakaian. Sebagai ustaz keturunan Yaman—habib pula—orang berharap ayah saya memakai jubah putih dan kopiah putih juga ala habaib. Tetapi, ayah saya selalu menolak. Pakaiannya tak pernah berubah, yakni pakaian umumnya ustaz Indonesia.
Bahkan, bukan itu saja. Ayah saya berada di antara pengambil keputusan dalam perubahan nama sekolah yang dipimpinnya, dari nama berbau Arab ke nama asli Indonesia. Sekolah, yang juga ikut didirikan oleh ayahnya itu, yang asalnya bernama Rabithah al-Alawiyah—perkumpulan kaum Alawi, yakni keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang merupakan cucu Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, migran pertama dari keturunan Nabi Saw. dari Irak ke Hadhramaut— menjadi Sekolah Diponegoro. Belakangan malah beliau meninggalkan Solo dan Kelurahan Pasar Kliwon—sebagai wilayah “kampung Arab”, tempat kelahiran dan telah lebih dari 50 tahun menjadi tempat tinggalnya—untuk pindah ke Bandung dan sepenuhnya mendedikasikan waktunya untuk pendidikan keagamaan bersama jamaah yang nyaris tak lagi beridentitas Arab.
Bahkan, di antara alasan hijrahnya itu adalah kurangnya kesejalanan dengan sebagian kelompok keluarga besar Alawiyyin terhadap pemikiran-pemikirannya yang sedikit banyak tidak “ngarabi” dan tidak “ngalawiyini”. Malah, sebaliknya, beliau justru cukup kritis kepada gejala penguatan symbol-simbol kearaban dan ke-alawiyah-an meski beliau masih tetap berupaya berkontribusi bagi kemajuan masyarakat yang merupakan keluarga besar biologisnya ini—termasuk terlibat dalam kegiatan ilmiah penerjemahan karya-karya tulis para ulama Alawiyyin, antara lain karya-karya Habib Abdullah al-Haddad1—lebih semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab kekeluargaan, yang memang selayaknya ditunaikannya. Mayoritas jamaah beliau di Bandung adalah mahasiswa-mahasiswa ITB, Unpad, dan universitas-universitas lainnya di kota itu.2
Alhasil, bagi keluarga kami, tak pernah ada keraguan sedikit pun bahwa kami adalah orang Indonesia. Bukan saja kami merasa sebagai orang Indonesia, kami bahkan tak pernah secara sadar merasa atau membawa diri sebagai orang “Arab” keturunan migran. Pergi ke Yaman pun saya belum pernah; begitu juga saudara-saudara saya yang lain. (Penulis buku ini pun rasanya belum pernah ke sana.)
Ayah saya, sebagai anak tunggal, memang pernah sekali diajak ayahnya ke Hadhramaut, untuk selanjutnya berencana bersekolah di Al-Azhar, Mesir. Bahkan, kakek saya sempat terpikir untuk kembali tinggal di Hadhramaut sambil tetap bisa dekat dengan anak tunggalnya yang direncanakan bersekolah di Mesir. Maklum, istri (pertama) beliau di Indonesia belum lama meninggal dunia, sedangkan beliau masih memiliki keluarga pertamanya di Hadhramaut— sebelum migrasi ke Indonesia. Tetapi, masa-masa tinggal di Indonesia telah begitu berkesan, bahkan di hati kakek saya, sehingga prospek tinggal kembali di Hadhramaut sama sekali sudah tak menarik baginya. Bahkan, negeri kelahirannya itu sudah tak lagi menjadikan masa pendek “percobaan” tinggalnya di sana menyenangkan. Ingat, kakek saya itu adalah seorang wulaiti (Yaman asli, kelahiran Yaman). Jadi, jangankan generasi saya atau generasi ayah saya, bahkan kakek saya pun lebih merasa nyaman dan belakangan lebih mencintai tinggal di Indonesia ketimbang negeri kelahirannya sendiri. Maka, setelah hanya beberapa bulan di sana, kakek saya memutuskan pulang dan tanpa ragu tinggal di Indonesia sampai akhir hayatnya.
Sesungguhnya banyak orang keturunan Yaman di Indonesia punya perasaan yang sama. Mereka lebih mencintai dan merasa diri sebagai orang Indonesia ketimbang orang Yaman—meski tak sedikit yang tetap menyimpan kerinduan alami untuk, setidaknya, pernah berkunjung ke sana. Bahkan, kaum Alawiyyin/habaibnya—dan ini berbeda dengan Alawiyyin di Malaysia atau Singapura, misalnya—tak ada lagi yang menyematkan gelar sayid di depan namanya.
Gelar habib pada masa itu hampir-hampir hanya disematkan kepada ulama kelahiran Hadhramaut atau yang pernah tinggal lama di sana. Itu pun hanya dari kelompok ulamanya. Maka, perlu ditegaskan di sini bahwa kecenderungan meng-Arab dan meng-habib di kalangan keturunan Yaman di Indonesia ini khususnya Alawiyyin adalah hal yang relatif baru. Sebuah gejala yang bisa dibilang “mundur” kepada apa yang oleh penulis buku ini disebut sebagai “Ilusi Identitas Arab”. Sebab, sebelum-sebelumnya, selama berabad-abad, para keturunan Yaman ini sesungguhnya telah hidup membaur dengan orang asli/pribumi Indonesia—meski istilah orang asli/pribumi ini pun sesungguhnya amat problematik juga (mana ada orang “asli”? Apalagi setelah teknologi DNA membuktikan bahwa sesungguhnya setiap orang terlahir sebagai campuran ras berbagai bangsa).
Sejak Wali Songo—setidaknya sebagian besar dari mereka—hingga Syaikh Siti Jenar dan tak sedikit ulama besar pembawa Islam ke Nusantara lainnya, mereka disebut-sebut sebagai keturunan kaum Alawiyyin dari keluarga Azmatkhan (keturunan Abdul Malik bin Ammul Faqih, yang merupakan keturunan ke-6 dari Alwi bin Ubaidillah, nenek moyang kaum Alawiyyin yang sudah saya sebut tadi). Lalu, ada lagi gelombang kedua migrasi orang-orang Yaman yang begitu terampil membaur sehingga mereka sampai diadopsi ke dalam keluarga raja-raja Nusantara melalui “perkawinan silang”. Bahkan, belakangan, mereka sendiri—atau keturunan-keturunan mereka—didapuk menjadi raja-raja di berbagai wilayah Nusantara.
Kiranya, sebagaimana diungkapkan oleh buku ini, awalnya peng-Arab-an adalah “jebakan batman” pemerintah kolonial Belanda yang tak ingin keturunan Arab (baca: Yaman)—yang dihormati di Nusantara—berpihak kepada gerakan perlawanan “pribumi”. Dengan kata lain, Belanda berupaya keras memisahkan keturunan “Arab” dari “pribumi”. Upaya itu memang tidak selalu berhasil. Selalu ada orang-orang yang kemudian justru memperkuat gerakan perlawanan bangsa Indonesia tersebut, termasuk para pendiri Jamiat Kheir yang amat nasionalis itu. Dan belakangan ada kelompok Partai Arab Indonesia (PAI) maupun juga kelompok non-PAI yang lebih tradisional, yang ternyata tak kalah nasionalisnya dari kedua kelompok yang disebut pertama.
Sayangnya, sebelum kekuatan nasionalis dari keturunan Yaman itu benar-benar telah mencapai posisi final nasionalistik yang tak bisa balik lagi (irreversible), muncullah sebuah gejala baru atau sebuah arus baru yang tidak sejalan. Sumbernya adalah suatu perkembangan yang sebenarnya amat baik di Hadhramaut, yakni bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan yang relatif modern di sana. Yang terkenal di antaranya adalah Rubath Tarim di bawah kepemimpinan Habib Abdullah bin Umar al-Syathiri; Darul Musthofa di bawah kepemimpinan Habib Umar bin Hafizh; dan Universitas al-Ahqaf yang didirikan oleh Habib Abdullah bin Mahfuzh al-Haddad.
Bersama dengan masuknya arus para sayid yang bersekolah dan lulus dari Iran—dan membawa mazhab Ahlul Bait yang juga memuliakan keturunan Nabi—masuk pulalah arus lulusan dari sekolah-sekolah di Hadhramaut tersebut. Sebetulnya ada juga arus masuknya para keturunan Arab asal Indonesia lulusan sekolah-sekolah di Arab Saudi dan Yaman. Tetapi yang ini beraliran Salafi, dan nyaris merupakan antitesis aliran keagamaan kaum Alawi. Tetapi arus ini pun, melalui jalur berbeda, ternyata ikut memperkuat kecenderungan kearaban melalui ajaran Salafiyah yang mereka bawa.
Memang aliran Salafiyah menganggap bahwa ajaran Islam yang murni adalah ajaran Islam yang dikembangkan oleh para ulamanya sampai abad ke-2 H dan bahwa Muslim harus selalu merujuk ke era ini. Dengan kata lain, mayoritasnya adalah ulama-ulama “Arab”. Jadi, lagi-lagi, sejak awal aliran ini sudah serba-kearaban dan akan terus demikian. Adanya arus baru “versi” Islam dari Yaman melalui kalangan habaib ini—dengan segala simbol kearaban/kehabibannya (juga Salafiyahnya)—secara cepat bisa merebut tempat dalam panggung dakwah Islam di Indonesia.
Hal ini dipermulus dengan adanya kepercayaan tradisional di kalangan NU—yang merupakan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia—tentang kemuliaan keturunan Nabi Saw. dan keharusan taat kepada mereka. Tanpa bermaksud mereduksi persoalan, apalagi bersikap sinis, dukungan masyarakat Muslim Indonesia ini sekaligus menguntungkan para pembentuk arus baru ini dalam memastikan posisi sosial-ekonomi yang baik bagi mereka. Apalagi, pada kenyataannya, memang ada gejala kecenderungan penurunan pencapaian sosial-ekonomi di kalangan keturunan Yaman di negeri ini.
Saya sama sekali tak ingin mengatakan bahwa para ustaz keturunan Yaman ini telah berupaya memanipulasi orang dengan keustazannya demi mencari uang—meski penipu model ini selalu ada di kelompok mana pun—tetapi bahwa unsur keagamaan, sekali lagi, bertemu dengan unsur sosial-ekonomi di sini. Kita memang tak bisa menyatakan bahwa dengan demikian keturunan Yaman pada masa ini telah memisahkan diri dari pribumi dan menjadi eksklusif. Tidak demikian. Bukan saja mereka pada kenyataannya telah berusaha membaur, bahkan mereka diterima dengan sangat baik oleh “pribumi”—setidaknya di kalangan cukup banyak kelompok masyarakat ini.
Meskipun demikian, pada saat yang sama, mereka seperti memperkuat identitas kearaban atau kehabiban mereka. Betapa tidak, bukankah identitas ini yang menyebabkan mereka diterima dan mendapatkan tempat yang baik di negeri Nusantara ini—dengan cara yang relatif mudah dan tak banyak membutuhkan kerja keras (labour) intelektual dan aktivistik, sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka pada zaman migrasi awal sampai sebelum abad ke-19-an itu?
Keberlangsungan hal ini didahului oleh terjadinya proses reifikasi terhadap ajaran Thariqah Alawiyah. Reifikasi di sini maksudnya adalah sesuatu yang mulanya lebih abstrak—yakni, yang memuat dasar-dasar spiritualitas yang kaya—kemudian direduksi/dikodifikasi menjadi hanya hal-hal yang konkret dan rigid. Bisa dalam bentuk institusi-institusi dan ritus-ritus yang distandarkan, serta gagasan-gagasan lain yang berwujud material—yang didasarkan pada kredo-kredo yang ketat. Dalam hal Thariqah Alawiyah, reifikasi ini mengambil bentuk Haddadiyah—yang awalnya dirumuskan oleh Habib Abdullah al-Haddad, seorang pembaru agung pada zamannya, untuk suatu tujuan yang sangat spesifik, yaitu standarisasi ajaran untuk awam—menjadi dianggap identik dengan Thariqah Alawiyah secara keseluruhan, yang sejatinya lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Reifikasi itu mengambil bentuk reduksi thariqah— mengikuti klasifikasi Habib Abdurrahman bin Abdillah Bilfagih—yang tak lain adalah salah satu murid utama Habib Abdullah al-Haddad sendiri—ke dalam dominasi ilmu raqâiq (ilmu tentang hal-hal yang bersifat lahir) dengan korban ilmu haqâiq (ilmu hakikat/spiritual)3. Memang ini juga mudah dijelaskan. Yakni, bahwa reifikasi ini lebih mempermudah dan meringankan bagi para ustaz dari kalangan Alawiyyin dalam upaya (labour) mereka untuk menyebarkan pengaruh dan mendapatkan pengikut.
Saya tak akan lagi berpanjang-panjang dengan kata pengantar ini. Namanya juga kata pengantar. Maka, baiklah, saya silakan para pembaca untuk mendaras buku yang mencerahkan dan membuka mata kita ini tentang fenomena kearab-araban yang menguat belakangan ini di negeri kita. Bukan saja penulis ingin menyatakan bahwa fenomena ini merupakan suatu kemunduran bagi kaum keturunan migran Hadhramaut (Yaman), tetapi identitas kearaban yang mereka gotong-gotong itu sesungguhnya secara historis adalah sebuah ilusi.
Identitas Arab sesungguhnya, menurut penulis buku ini, adalah identitas penutur bahasa Arab. Pendeknya, Arab adalah suatu kategori bahasa, bukan ras, apalagi ras unggul. Arab meliputi berbagai bangsa dan ras yang berbeda-beda, persis seperti bangsa-bangsa dan ras-ras lain. Maka, menegaskan identitas Arab seolah-olah ia sebagai suatu identitas monolitik bukan saja suatu kemunduran, melainkan juga kesalahan. Malah hal itu bisa menjadi kontraproduktif bagi perkembangan dakwah Islam serta kesatuan dan integritas bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia telah memiliki identitas kenusantaraan, yang bukan cuma luhur, tetapi juga sejalan dengan ajaran para habib itu. Bukankah interaksi antara bangsa Nusantara dan bangsa Yaman (Hadhramaut) sudah terjadi bahkan sejak sebelum masa Wali Songo, yakni pada abad ke-12/13 bersama kunjungan Syaikh Mas‘ud al-Jawi ke negeri itu?4 Dan bukankah sejak itu sesungguhnya pengaruh pemahaman Islam di Hadhramaut sudah bekerja dalam perkembangan pemikiran Islam di Nusantara melalui Wali Songo dan para ulama pada era yang sama? Juga pada era perkembangan paham Martabat Tujuh Wujudi atas banyak ulama Islam sejak Makassar (Syaikh Yusuf al-Makassari), Aceh (setidaknya pada Syaikh Nuruddin al-Raniri dan para muridnya), sampai Jawa (Syaikh Muhyiddin, K.H. Hasan Mustapa, dan lain-lain), hingga masa-masa sebelum pendirian NU sampai sekarang ini, yang di dalamnya para pendiri dan tokoh NU belajar dari para ulama habib dari Yaman dan memakai buku-buku karya mereka di pesantren yang mereka kembangkan?5
Maka, bukan saja sudah seharusnya identitas keindonesiaan ini dipelihara sebagai identitas sejati para keturunan Yaman di Indonesia, pada kenyataannya identitas kenusantaraan pun sudah mengapropriasi identitas keyamanan, setidaknya di bidang pemahaman keislaman. Dan para keturunan Yaman, yang mayoritasnya bukan penutur bahasa Arab asli, sudah seharusnya menegaskan dirinya sebagai pemilik identitas tunggal Indonesia: secara tegas, tidak ambigu, dan bukan lips service saja sebagaimana banyak terkesan selama ini.
Sedikit catatan: mungkin sampai di sini muncul pertanyaan, jika identitas sebagai keturunan Arab—dalam hal ini, identitas sebagai sayid/habib—dibaurkan, apakah tidak berarti hal ini akan menghambat peran para sayid/habib dalam mewujudkan wasiat Nabi bahwa ‘itrah/Ahlul Bait (yakni, keturunan Nabi) adalah salah satu dari al-tsaqalain (dua hal yang berat/serius) sebagai sumber petunjuk yang tidak akan pernah terpisah dari Al-Qur’an sampai akhir zaman? Saya kira jawabnya: tidak. Para keturunan Nabi yang memiliki kapasitas keulamaan—yakni, memiliki kedalaman ilmu dan ketinggian maqâm keruhanian—mestinya tetap saja akan muncul dan diakui masyarakat secara alami karena otoritas yang mereka miliki sebagai sumber petunjuk itu, tanpa harus menegaskan—apalagi membutuhkan pengakuan akan—identitas mereka secara khusus sebagai keturunan Nabi (“Arab”), lebih-lebih melalui propaganda, terang-terangan atau secara simbolik, oleh para keturunan Nabi itu sendiri. Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dan ketinggian maqâm spiritualitas seperti ini, bisa dibayangkan, akan dengan sendirinya mendapat pengakuan dari masyarakat dan diterima sebagai pemandu bagi masyarakat itu sebagaimana semua ulama, bahkan yang bukan keturunan Nabi (“Arab”). Apalagi, jika memang keturunan Nabi adalah salah satu dari wasiat peninggalan Nabi yang akan selalu terkait dengan Al-Qur’an sebagai sumber petunjuk, maka tentu saja tidak akan ada yang dapat menghalangi kemunculan dan peran mereka di tengah masyarakat.
Keberatan lain yang mungkin timbul apabila identitas simbolik sebagai keturunan Nabi dihilangkan adalah kesulitan menjalankan beberapa perintah syariah—sebagaimana diyakini dalam sebagian mazhab tertentu. Termasuk, menurut setidaknya sebagian dari Mazhab Syafi‘i, bahwa keturunan Nabi yang miskin tidak diperbolehkan menerima zakat (kecuali dari sesama keturunan Nabi). Karena itu, identitas mereka perlu dipelihara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan syariat ini.
Contoh kedua menyangkut soal kafaah. Prinsip ini mewajibkan syarifah (perempuan dari keluarga keturunan Nabi), lagi-lagi menurut pemahaman sebagian Mazhab Syafi‘i dan yang lain, tidak diperbolehkan menikah dengan non-sayid.
Masalah-masalah di atas sesungguhnya bisa diatasi cukup dengan adanya praktik atau tradisi mencatat dan memvalidasi silsilah atau nasab para keturunan Nabi ini melalui sebuah kantor yang memang secara khusus bertugas melakukan hal ini. Di Indonesia, misalnya, tugas ini diselenggarakan secara bisa dipertanggungjawabkan oleh Maktab al-Da’imi. Dengan pencatatan semacam ini tentunya kemungkinan bagi kerancuan atau pelanggaran terhadap perintah syariah—menurut mazhab atau ulama yang memiliki pandangan seperti ini—akan bisa dihindari. Sambil lalu, perlu saya sampaikan di sini bahwa dengan mengatakan ini semua, tak berarti saya anti terhadap semua saja simbol keulamaan umum yang sudah diapropriasi (diserap) ke dalam budaya Nusantara, meskipun itu berasal dari Timur Tengah. Seperti kita ketahui, sebagian simbol Arab-Islam sesungguhnya sudah lama diadopsi oleh budaya Nusantara, termasuk dalam hal pakaian. Toh, budaya Indonesia juga sudah mengadopsi budaya yang sama dari Barat, Cina, India, dan lain-lain tanpa masalah. Yang lebih saya persoalkan dalam kata pengantar ini adalah anggapan bahwa apa-apa yang serba-Arab adalah lebih autentik-Islam sehingga perlu dikukuhkan dan diunggulkan sebagai identitas eksklusif, lengkap dengan segala simbol dan aura khasnya—termasuk gestur (gerak-gerik), gaya berpakaian khas Arab (non-Nusantara) yang mencolok, puja-puji melangit, pengunggulan tokoh-tokoh dan hal-hal yang serba-Arab, dan sebagainya—sambil terkesan menganggap kalah keren identitas kenusantaraan atau keindonesiaan. Seolah-olah semuanya itu bagian dari keunggulan ajaran Islam atau tanda-tanda keunggulan keislaman seseorang. Jangankan Arab secara umum, bahkan kesayidan tak otomatis menjadikan seseorang memiliki keunggulan dalam hal keagamaan. Seperti dituliskan juga dalam buku ini—dan ini dibenarkan oleh para tokoh besar di kalangan kaum sayid sendiri—kesayidan hanya relevan jika dia membawa bersamanya ciri-ciri kebaikan agama, termasuk ilmu, spiritualitas, dan akhlak mulia. Karena, pada puncaknya, kebaikan Muslim—siapa pun dia—hanya dilihat dari kriteria-kriteria yang tersebut barusan. Dan kriteria-kriteria itu pun tak bisa diukur hanya dengan penampilan rasistik, dinastik, atau simbolik, meskipun berpenampilan serba-Arab atau habib.
Akhirnya, meski penulis buku ini sudah memberikan disclaimer bahwa buku ini lebih merupakan sebuah eksplikasi fenomenologis—penjelasan yang diupayakan bukan terutama melalui teori-teori, melainkan lebih dari pengalaman atau keterlibatan langsung, intim, dan empatik dengan perhatian terhadap soal yang dibahas—ketimbang sebuah karya ilmiah berdasarkan penelitian mendalam, tak urung buku ini merupakan suatu autokritik dan analisis tajam yang membuka mata tentang isu yang dibahasnya. Diharapkan seluruh elemen bangsa Indonesia—baik yang selama ini disebut “keturunan Arab” maupun yang biasa disebut “pribumi”—bisa mengambil manfaat darinya dalam upaya meluruskan dan menjernihkan kesadaran dan persepsi mereka semua tentang identitas kearaban. Dengan demikian, diharapkan lahir sikap dan pandangan yang proporsional, lurus, dan konstruktif bagi perkembangan Islam dan kebangsaan di Indonesia. Selamat. Semoga juga penulisan buku ini membawa banyak berkah bagi Sdr. Musa Kazhim Alhabsyi sebagai penulisnya, dan selamat menikmati serta mengambil manfaat bagi semua pembaca.[]
___________
1 Saya pun, meski berpandangan bahwa kaum habib harus bersikap lebih membaur dan menjadi lebih Indonesia, bukannya kemudian menjadi tidak peduli terhadap legacy (turats) kaum Alawiyyin. Saya bahkan ikut dalam pendirian dan penyelenggaraan organisasi MAHYA (Majelis Hikmah Alawiyah), yang bergerak di bidang penghimpunan dan penelitian serta diseminasi karya-karya ilmiah kaum habib/Alawiyyin. Bagi saya, ini adalah suatu kontribusi dan tanggung jawab ilmiah—dan sekaligus tanggung jawab dakwah—yang sudah seharusnya dilakukan siapa saja dalam rangka memelihara kekayaan ilmiah Islam dengan karya-karya yang baik dari kelompok mana pun, dalam hal ini dari kelompok Alawiyyin/ habaib.
2 Kisah Muhammad Bagir Alhabsyi dan ayahnya (Hasan Alhabsyi) dapat dibaca dalam buku biografi Sang Penggugat dari Pasar Kliwon: Biografi Muhammad Bagir Alhabsyi, susunan Mustofa Najib, yang dijadwalkan terbit April 2022.
3 Ulasan lebih jauh tentang hal ini dapat dibaca dalam tulisan Haidar Bagir berjudul “Thariqah ‘Alawiyah dan Tasawuf Filosofis (‘Irfân)”.
4 Silakan baca https://islamindonesia.id/haidar-bagir/kolom-haidar-bagir-peran-habaib-dalam-pengembangan[1]islam-nusantara.htm.
5 Lihat tulisan Haidar Bagir berjudul “Napas Cinta dari Hadhramaut dan Jaringan Ulama Nusantara dengan Ajaran para Habaib Sepanjang Sejarah: Sebuah Outline, serta Peran Habaib dalam Pengembangan Islam Nusantara” dalam Majalah Tempo, 12 Agustus 2012.