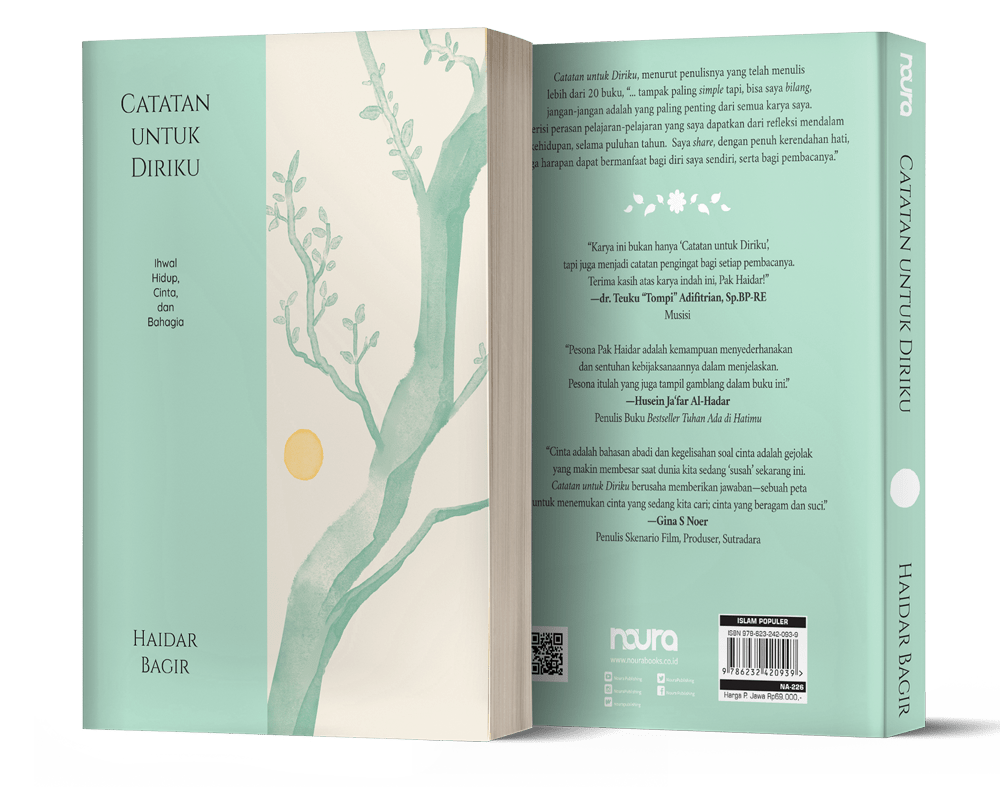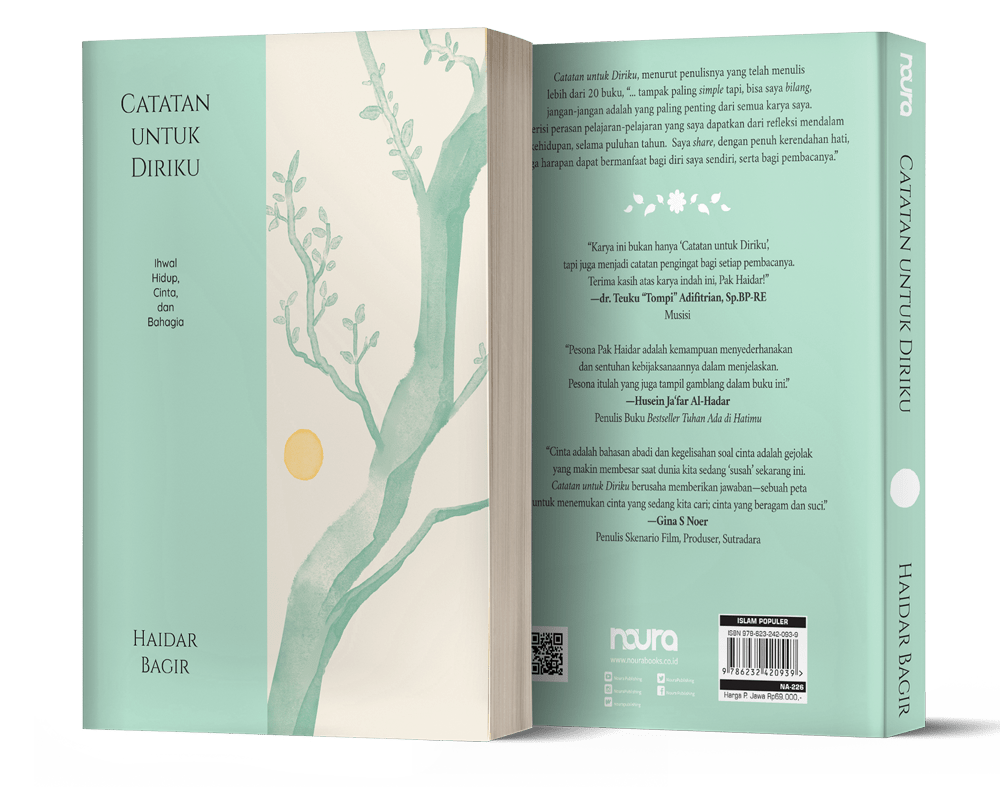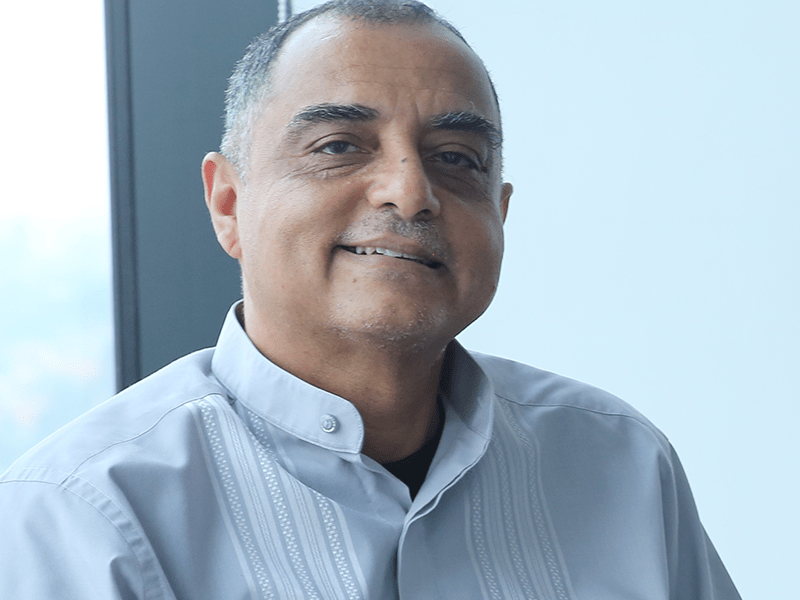Waktu itu kira-kira tahun 1977 atau 1978. Tak kurang dari 43 atau 44 tahun lalu. Umur saya baru sekitar 20 tahunan. Entah karena masih berada dalam suasana psikologis anak muda di masa pancaroba, atau memang saya bertemperamen melankolik, atau bahkan depresif. Saya mengalami semacam krisis psikologis. Hampir-hampir tak ada sama sekali alasan riil—paling tidak yang saya sadari. Hidup saya berjalan lancar-lancar saja, bahkan terlalu lancar. Saya kuliah di ITB, malah sempat kuliah rangkap di UNPAD. Meski bukan berasal dari keluarga berlimpah harta, tapi saya tak pernah benar-benar memiliki masalah finansial. Bisa jadi karena orang tua saya—ayah saya—memang telah melakukan apa saja untuk memastikan support bagi kehidupan anak-anaknya, betapa pun mungkin bisnisnya didera pasang-surut. Saya pun rasanya bukan misfit di lingkungan saya. Saya tak pernah defisit teman, dan punya sahabat-sahabat dekat yang mendukung—sampai batas tertentu bahkan cukup populer di lingkungan saya.
Tapi entah kenapa, suatu saat di tahun-tahun itu, rasa sumpek tiba-tiba saja menyergap. Begitu saja, almost out of nowhere. Saya merasa gelisah, hidup seperti kehilangan makna. Kadang saya menghabiskan waktu nonton film di bioskop, dan justru memilih film-film yang tidak populer, hanya agar saya bisa berada dalam kesepian bioskop yang kosong.
Baca Selengkapnya
Maka, saya—yang memang sudah mengembangkan kebiasaan membaca buku—tak pelak mulai lari ke buku-buku lumayan berat. Saya ingat membaca buku Reconstruction of Religious Thought in Islam karya pujangga anak-benua India, Muhammad Iqbal. Sebuah buku yang cukup rumit. Dari situ saya pun mengenal Varieties of Religious Experience karya filsuf-psikolog top Amerika, William James. Juga sebuah buku yang amat rumit. Dari situ menyusul buku-buku filsafat yang tak kalah berat. Ada karya Arif Budiman, Chairil Anwar, Sebuah Pertemuan, atau Heteronomia karya Fuad Hassan. Di luar itu saya pun menonton film-film non-komersial serius di Kine Club Bandung, plus mengikuti pemikiran sastra dan seni. Tak jarang saya mengunjungi pameran-pameran seni. Saya ingat, termasuk pameran Gerakan Seni Rupa Baru di TIM.Demikianlah, mood saya menyeret saya kepada apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran filosofis dan karya-karya seni lumayan berat. Di tengah ketertenggelaman di dalam karya-karya semacam itu—saya lupa, entah dari mana—saya mendapatkan sebuah buku perenungan personal yang amat memikat dan hampir sepenuhnya beresonansi dengan situasi saya saat itu, berjudul Notes to Myself, My Struggle to Become a Person, karya Hugh Prater (belakangan saya juga membaca karya lain sejenis dari penulis yang sama, berjudul Spiritual Notes to Myself. Essential Wisdom for the 21st Century). Buku ini tak bisa dibilang ringan. Tapi, karena sifatnya yang personal, dan ditulis dengan bahasa emosional yang mengalir, buku ini terasa tak terlalu sulit saya serap. Apalagi cetusan-cetusannya yang ditulis pendek-pendek, hampir-hampir berupa kesimpulan dari perenungan-perenungan panjang dan mendalam.
Segera saja saya jatuh cinta kepada buku ini. Rasa sumpek itu pun tak terlalu lama kemudian pergi juga. Saya pun jadi anak muda yang kembali menjalani hidup dengan gembira dan penuh harapan. Sesekali rasa sumpek datang dan pergi. Tapi kecenderungan saya untuk selalu merefleksikan dan memeras makna dari apa yang terjadi dalam hidup saya—kesedihan, simpati pada orang-orang susah, kebosanan, dan ketidakadilan—sudah kadung mendarah daging. Lebih sering tidak saya tulis. Tapi tampaknya selalu laten.
Ya, seingat saya, sejak saat itu saya mulai mencoba mencoret-coretkan perenungan-perenungan saya dengan gaya yang saya adopsi dari gaya penulisan buku Notes to Myself itu. Yang pasti, sejak 40 tahunan yang lalu itu saya sudah membayangkan diri saya menerbitkan karya sejenis Notes to Myself. Suatu saat, entah kapan. Ringkas, menukik, penuh kelembutan dan kedalaman emosi, yang mengakar dan, berkat semua ramuan itu, berdaya transformatif.
Puluhan tahun setelah itu saya kira saya sudah mulai lupa pada keinginan saya tersebut. Tapi, kecenderungan saya kepada perenungan-perenungan personal tentang makna hidup, rasanya tak pernah benar-benar surut. Hingga suatu saat saya diminta oleh salah satu stasiun radio Lite FM di Jakarta, untuk mengasuh sebuah acara tentang kebahagiaan, setiap Jumat pagi. Tak kurang dari 4 tahun saya mengasuh acara ini. Pernah pula sebuah stasiun TV swasta meminta saya menjadi pembicara pamungkas, yang menyampaikan kesimpulan-kesimpulan reflektif dari sebuah acara dokumenter bernuansa human interest, yang merekam perjuangan orang-orang kecil. Bagian saya mungkin hanya berdurasi 2 menit saja, di akhir acara. Tapi justru ini menjadi peluang lain bagi saya untuk mencurahkan dorongan menjalin perenungan-perenungan personal yang memang sudah menjadi kerinduan saya sejak lama itu.
Sesekali saya menulis puisi. Rasanya tak bagus-bagus amat juga. Di kali lain saya membuat semacam cerpen, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai esai dengan sentuhan sastrawi. Tak pernah saya berupaya menerbitkannya, lagi-lagi karena saya tak yakin akan kualitasnya.
Sampai di suatu saat, mungkin bermula mulai 6-7 tahun lalu, saya memaksa diri untuk ikut-ikutan ber-Twitter ria. Seorang teman membuatkan akun. Saya pun sempat mencoba menuliskan perenungan-perenungan pendek dalam medium sosial baru ini. Tapi baru sebentar memulai, saya pun berhenti menulis. Hingga mungkin setahun-dua setelah itu, saya mulai benar-benar aktif ber-Twitter. Kadang saya bicara politik, lebih sering agama, tapi porsi terbesar cuitan-cuitan saya selalu bersifat perenungan personal tentang hidup dan maknanya, tentang cinta, kebahagiaan dan kebaikan hati.
Tak lama terbukti banyak orang menyukai perenungan-perenungan personal saya tersebut. Follower saya dalam waktu tak terlalu lama meningkat pesat. Pada tahun-tahun pertama saya masih merasa terkendala dalam menjadikan medium ini mampu merekam perenungan-perenungan personal saya dengan baik, antara lain karena pembatasan karakter yang terlalu ketat oleh Twitter. Hingga suatu saat Twitter memutuskan melipatduakan jatah jumlah karakter untuk setiap cuitan. Percaya atau tidak, Twitter seperti benar-benar tahu tentang berapa jumlah karakter yang diperlukan untuk keperluan penulisan genre ini. Batas jumlah karakter yang baru itu memang tidak terlalu sedikit sehingga mampu menampung ungkapan yang bermakna jelas. Tapi, pada saat yang sama, pembatasan jumlah karakter itu juga memaksa penggunanya untuk benar-benar mampu memeras cuitannya ke dalam suatu sari pati yang justru mengetuk hati karena sifat ringkasnya. Seperti sebuah gong di akhir penggalan-penggalan lagu dalam konser gamelan. Efisien, dan menusuk tepat ke lubuk jantung pembacanya. Setidaknya begitu yang saya bayangkan, dan saya bayangkan dirasakan oleh follower akun Twitter saya.
Saya kira saya juga berutang pada Twitter dalam hal melancarkan luncuran ungkapan-ungkapan yang reflektif, nyaris puitis, dari dalam hati saya. Terbukti para pengguna Twitter menyukainya—tampak dalam terus meningkat pesatnya jumlah follower. Sebenarnya cuitan-cuitan saya tak bisa dibilang ringan, terkadang malah filosofis bahkan mistis. Tapi kenyataannya jumlah follower saya meningkat lebih cepat. Nyaris saya tak pernah bercanda di Twitter, atau membahas pertandingan-pertandingan sepakbola yang digandrungi para pengguna Twitter. Apalagi berantem, yang sudah seperti menjadi “penyakit” bawaan media sosial ini. Sebuah penyakit yang ternyata justru banyak disukai orang. Alhasil, sekarang follower saya sudah mendaki menuju angka 200 ribu orang. Dan jumlah cuitan-cuitan saya pun makin lama makin banyak. Sebagian besar di antaranya berupa refleksi-refleksi personal tentang hidup, kebahagiaan, cinta, dan kebaikan hati.
Lalu suatu saat seorang pimpinan di Noura, salah satu unit penerbitan Mizan, menyatakan ketertarikannya untuk membukukan perenungan-perenungan personal saya tersebut. Meski bukan sama sekali tak dikerjakan, perkembangan persiapannya berjalan lambat. Antara lain karena saya pun tak begitu antusias menyambut gagasan tersebut. Hingga suatu hari, seseorang datang kepada saya, membawa mock up cukup lengkap buku yang berisi kumpulan permenungan-permenungan personal itu.
Namanya Mas Deni. Seorang seniman dan pejalan, pencinta Iwan Fals garis keras. Dia sebetulnya adalah juga salah seorang staf di Yayasan Filantropi kami. Sambil menyerahkan mock up tersebut, Mas Deni bercerita bahwa motivasinya mengumpulkan renungan-renungan saya itu adalah perasaan terbantu dalam menjalani salah satu krisis yang menerpa kehidupannya dengan membaca dan merenungan refleksi-refleksi personal saya itu. Saya tak urung senang meski tetap agak enggan. Tapi, betapa tak berperasaannya saya jika saya menolak keinginan yang begitu lembut dari seseorang yang berniat baik seperti itu.
Maka mock up itu pun saya serahkan ke Penerbit Noura, yang tanpa berlama-lama kemudian mengolahnya, dibantu asisten saya, Sdr. Azam Bahtiar. Setelah itu, calon buku ini masih harus melewati banyak tahap penyempurnaan. Sehingga, ketika draf yang sudah lebih sempurna kembali kepada saya, tak ayal memori kerinduan saya 40 tahun lalu itu seperti kembali hinggap di benak. Inilah tampaknya wujud mimpi saya waktu itu untuk suatu saat bisa menulis Notes to Myself versi saya sendiri.
Maka, kini tanpa keraguan sedikit pun, buku ini saya juduli Catatan untuk Diriku, yang tak lain adalah terjemahan apa adanya dari judul buku yang dulu sempat ikut membentuk diri dan pemikiran saya itu. Setelah ditambah-kurangi di sana sini, lalu lebih disistematisasikan, serta ditambah bahan-bahan lain renungan saya yang tersebar di berbagai grup WhatsApp, termasuk juga bahan-bahan dari buku kecil yang pernah saya terbitkan (sebagai komplimen bagi buku Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan—berjudul Percikan Cinta dan Kebahagiaan), siaplah buku ini untuk dicetak dan diluncurkan.
Buku mungil Percikan Cinta dan Kebahagiaan itu sendiri bisa saya katakan lebih populer ketimbang buku utamanya. Bukan saja banyak orang mengungkapkan secara langsung kepada saya bahwa mereka amat terbantu menjalani pasang surut kehidupan mereka oleh buku mungil itu, sebagian orang malah meminta saya mencetak khusus buku mungil tersebut. Bahkan ada juga yang memfotokopi atau meminta izin kepada saya untuk mencetak buku tersebut. Tentu saja saya senang. Sebenarnya, bahan-bahan yang ada di buku kecil itu pun berasal dari teaser-teaser yang saya tulis atau rekam bagi hampir 200-an episode acara radio yang saya ceritakan di atas. Pernah pula ia terbit sebagai dua buku kecil untuk suvenir perkawinan dua orang keponakan saya.
‘Alâ kulli hâl, buku yang ada di tangan pembaca ini adalah perasan dari refleksi-refleksi personal saya selama puluhan tahun. Dengan segala kerendahan hati, saya hanya berharap—sesedikit apa pun—bahan-bahan yang ada dalam huku ini bisa ikut membantu para pembaca yang budiman untuk melewati pasang surut kehidupan, serta merawat kebahagiaan hidup betapa pun pancaroba kehidupan selalu megharu-biru kehidupan kita.
Terima kasih, Mas Deni. Kalaupun buku ini hanya membantu Mas Deni, saya merasa nilai buku ini sudah sangat tinggi. Apalagi jika ternyata lebih banyak orang merasakan manfaat yang sama. Selamat membaca dan merenung. Selamat menemukan makna hidup, dan selamat berbahagia dalam cinta dan kebaikan hati.
Saudaramu,
Haidar Bagir