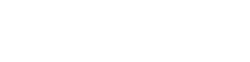Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
(QS Al-Hujurât [49]: 15)
Hari itu 27 Desember 2008, sebuah pesan pendek menghampiri telepon genggamnya.
Gaza dibom Israel!
Hati Joserizal Jurnalis terguncang. Dia mengernyit- kan dahi, mengamati layar telepon genggamnya dengan saksama. Sederet angka yang tak dikenalnya mengabarkan berita buruk itu. Nomornya berkepala +97… hmmm… apakah ini nomor Palestina?
Penasaran akan kebenaran SMS yang baru saja di- terimanya, Jose menyalakan televisi. Dipijit-pijitnya tombol remote, hingga matanya terpaku di kanal Al-Jazeera. Sekilas dia melirik jam dinding. Pukul 10 malam.
Layar TV menayangkan kondisi terakhir di Gaza. Penyiar tak henti membacakan berita terkini. Sedangkan di layar, Jose menyaksikan penduduk Gaza yang tersiksa. Ada yang terluka, gugur, ada pula yang melempari tentara Israel dengan batu, yang dibalas dengan berondongan sen- jata. Hatinya pedih melihat saudara-saudaranya menderita seperti itu.
Jose kemudian menyalakan radio. Di sana pun dia mendengar berita yang sama. Jose lalu mengontak beberapa teman untuk saling bertukar berita dan perkembangan terkini. Confirmed. Israel melancarkan serangan gila-gilaan di atas Jalur Gaza, Palestina. Serangan di luar perikemanusiaan, yang membuat siapa pun terenyuh dan ingin mengutuk.Al-Jazeera terus-menerus menyiarkan berita tentang serangan bertubi-tubi di wilayah yang dikuasai pemerintah Hamas itu. Satu serangan disusul serangan lainnya. Pemandangan yang membuat Jose geram. Hatinya terkoyak. Sebagai seorang dokter bedah tulang, dia tidak mungkin tinggal diam menyaksikan korban kebiadaban perang bergelimpangan. Terlebih karena korban-korban itu adalah saudaranya sendiri, sesama Muslim. Hatinya tak akan bisa tenang selama dia belum turun tangan. Pikirannya bekerja cepat: misi Palestina yang pernah disiapkan MER-C harus dihidupkan.
Jose masih memelihara keyakinan itu. Suatu hari, dia akan berangkat ke Palestina. Membantu rakyat Palestina adalah bagian dari kewajiban agama. Al-Aqsha adalah kiblat orang Islam pertama yang kini berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Al-Aqsha harus dibebaskan.
Pembebasan Al-Aqsha bukan berarti mengusir orang-orang non-Muslim, tetapi memberikan kesempatan kepada semua penganut agama untuk menghormati Jerusalem, seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khathab. Semua orang Yahudi dan Nasrani boleh beribadah ke sana. Mereka tidak dihalangi dan tidak dihambat seperti sekarang, seakan-akan Jerusalem adalah wilayah Israel.
Jose menganggap perjuangan orang-orang Palestina merebut kembali daerah-daerah mereka adalah perjuangan yang wajar, sebab memang mereka pemilik tanah tersebut. Mereka terusir setelah Israel masuk dengan bantuan Inggris ketika Perang Dunia II. Israel tidak mau hidup berdampingan. Zionis itu tidak mengizinkan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat memiliki angkatan bersenjata.
Konsep yang dikembangkan Israel hingga kini hanya menunjukkan arogansi mereka. Padahal, ketika menguasai Jerusalem, Islam memberikan hak yang sama, dan itu bukan omong kosong. Selain karena kewajiban agama,
Jose tidak ingin melupakan peranan Muslim Palestina bagi Indonesia, sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
Sambil menyimak Al-Jazeera, Jose sibuk berkomunikasi dengan anggota presidium MER-C. Dia juga menelepon Mursalin, sahabatnya dari Forum Umat Islam.
“Baik, saya setuju dengan pendapatmu,” kata Mursalin di ujung telepon.
“Ya, kita tidak boleh menunggu lagi. Saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan. Misi ini harus segera berangkat,” Jose menegaskan.
“Oke, mari kita laksanakan tugas masing-masing.” Hubungan telepon terputus. Kesepakatan terjalin.
Kini, keputusannya sudah pasti. Jose lalu menelepon dua stafnya, Islamiyah dan Rima. Islamiyah atau biasa disapa dengan Teh Iis adalah Ketua Divisi Logistik MER-C. Kepadanya Jose memerintahkan untuk mempersiapkan logistik Tim. “Kita akan mengirim misi ke Jalur Gaza, tolong siapkan logistik tim.”
Kemudian Jose segera menelepon Rima, Sekretaris Eksekutif MER-C, dan memintanya menyiapkan administrasi tim dan konferensi pers. “Kita akan konferensi pers malam ini juga. Bisa, kan?” tanya Jose.
Rima melihat kalender di mejanya. Oo … ini, kan, Sabtu. Apa mungkin mengundang wartawan malam ini? Akhir pekan biasanya karyawan libur atau mereka sedang di lapangan. Apalagi ini akhir tahun. Dengan perasaan tak enak, Rima mencoba membujuk Jose untuk menunda dulu. Di ujung telepon Jose menarik napas panjang. Dia mengakui usul Rima benar, meskipun berat menerimanya.
Rasanya dia sudah ingin terbang ke Gaza saja, kendati belum tahu caranya. Tapi semendesak apa pun, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang.
“Oke,” Jose mengalah, “temu persnya besok saja.”
Bagi Jose dan MER-C, rencana konferensi pers itu tak ubahnya kebulatan tekad karena mereka belum tahu bagaimana caranya bisa pergi ke sana. Soalnya, niat untuk memberangkatkan misi ke Gaza bukan pertama kali ini saja datang. Namun, mereka selalu terbentur masalah yang sama setiap hendak menjalankan misi spesial itu. Ya, tembok-tembok itu. Tembok yang bahkan lebih panjang dari Tembok Berlin.
Memasuki teritori yang sudah dua tahun diblokade pemerintah Israel bukan perkara mudah. Apalagi Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi Jose selalu yakin, niat dan ikhtiar akan menemukan jalan menuju kenyataan. Tuhan akan menolong manusia yang berusaha.
Hari belum berganti ketika jalan itu datang sendiri menghampiri. Ponsel Jose berdering nyaring. Betapa kagetnya Jose ketika menatap layar telepon, di sana tertera nama Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
“Assalamu‘alaikum, Bu? Apa kabar?” sapa Jose senang. “Wa‘alaikum salam, baik Jose,” sahut Siti Fadilah
ramah.
Sejak menjabat Menteri Kesehatan, Siti Fadilah memang kerap berkomunikasi dengan Jose untuk berdiskusi soal isu-isu penting di bidang sosial, politik, dan terutama politik kesehatan, misalnya kasus flu burung atau NAMRU, laboratorium milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Indonesia.
Menteri Kesehatan begitu antusias membicarakan serangan Gaza. Sebagai sesama dokter, Jose bisa merasakan gejolak batin yang serupa. Dia gembira Siti Fadilah merasakan gairah perjuangan yang sama.
“Jadi, kita bagaimana?” dari balik telepon, Siti Fadilah meminta pendapat.
“Ya, kita kirim tim ke sana. Jangan hanya mengirim bantuan uang saja, Bu,” ujar Jose dengan penuh harapan langkahnya kali ini mendapat jalan keluar.
“Betul itu, saya setuju.” Jawaban Siti Fadilah cukup melegakannya. Kini mereka satu suara. Dari pihak pemerintah, misi bantuan kemanusiaan ke Gaza itu murni sebagai inisiatif spontan Menteri. Sama sekali diputuskan tanpa rapat kabinet. Siti Fadilah lalu meminta Jose menghubungi dr. Rustam Syarifuddin Pakayya, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, untuk membicarakan masalah teknis keberangkatan ke Gaza.
Jose sendiri tidak habis pikir kenapa dia bisa cukup dekat dengan seorang menteri. Dia hanya bisa merenung, apabila seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas, dan berusaha lebih keras untuk ikhlas, Allah akan mempermudahnya bertemu dengan orang-orang yang memiliki gelombang keikhlasan yang sama. Formula itu hampir seperti rumus hidup bagi Jose. Rumus yang menyertai perjalanan hidupnya dan tertanam dalam alam bawah sadarnya, seolah ada radar yang bisa membedakan mana orang yang punya maksud buruk atau yang tulus. Saat radar itu mendeteksi hal yang tidak baik, sekalipun mereka sudah duduk berhadapan dan saling bicara panjang lebar, tetap saja ada yang tidak pas dengan suasana batinnya. Seperti ada hijab yang menghalanginya terlibat terlalu jauh dengan orang itu.
Sebaliknya, sepanjang pertemanan itu berlandaskan keikhlasan, Jose akan menjalaninya dengan nyaman. Tetapi, karena ikhlas adalah kondisi yang harus diusahakan, dia juga bisa menghilang. Pernah, suatu ketika dia berteman baik dengan seorang pejabat. Namun, menjelang akhir jabatan sang teman, mereka mendadak tidak sejalan. Pejabat itu mulai menjauh. Belakangan, dia mendengar kabar jika sang teman tersangkut kasus korupsi.
Berada di lingkungan orang-orang ikhlas membuat hidup Jose terasa nyaman. Dia bisa membuktikannya ketika MER-C menembus Afghanistan atau Irak. Padahal, Jose sama sekali tidak punya kontak dengan orang Taliban maupun orang Saddam Hussein. Tapi ternyata mereka bisa masuk ke Kandahar atas rekomendasi dari Salim Said, Duta Besar Taliban di Islamabad.
Ketika bertemu dengan Salim Zaid, penampilan Jose sama sekali tidak bergaya Taliban. Dalam pemberitaan internasional yang sering dibaca dan didengarnya, Taliban sering kali disebut-sebut fanatik dengan pakaian. Baju-baju ala Barat identik dengan baju kafir. Namun Jose malah menghadap dengan memakai baju biasa, setelan kemeja dan celana blue jeans, tanpa gamis dan serban. Dia lantas memperkenalkan diri sebagai ahli bedah.
“Saya dokter. Saya bawa uang, bawa obat, dan bawa tim. Saya mau ke Afghanistan,” ujar Jose kepada Salim Zaid. Untuk sesaat, lelaki berpengaruh itu menatap penampilan Jose. Matanya menyipit dan kemudian menghela napas. Dia mengajak Jose ngobrol tentang kondisi Afghanistan dan bertanya soal bantuan yang dibawa tim Indonesia. Keadaan yang darurat mungkin membuat Salim Zaid tidak perhitungan lagi soal penampilan, sebab tak lama berselang, keluarlah surat rekomendasi itu. Rekomendasi yang menjadikan MER-C sebagai organisasi nonpemerintah pertama yang bisa masuk Afghanistan, ketika peperangan melanda Kandahar untuk pertama kalinya.
Modal ikhlas juga dia pakai ketika MER-C hendak mengirimkan tim ke Irak. Ketika itu, Jose masuk ke Irak lewat pintu perbatasan Yordania. Visa masuk ke Irak yang dia urus di Amman bisa selesai dalam waktu lima jam saja. Padahal dalam keadaan permulaan perang, tak mudah bagi suatu negara untuk memberi izin masuk kepada orang asing dengan begitu saja. Walhasil, ketika sejumlah organisasi nonpemerintah masih mengantre izin masuk di perbatasan, MER-C berhasil melaluinya dan menjadi satu-satunya NGO yang masuk ke Irak di masa awal perang. Bukankah ini suatu anugerah?
Ketika berangkat ke Irak, Jose membeli obat-obatan di Damaskus, Suriah. Tapi, dia sedikit mendapat masalah ketika mengurus visa Suriah. Untuk memudahkan urusan, Jose mendatangi Kedutaan Besar Suriah di Amman, diantar staf Kedutaan Besar Indonesia. Sayang, usahanya tak membuahkan hasil. Pantang menyerah, keesokan harinya dia datang lagi dengan anggota tim MER-C, tanpa diiringi staf kedutaan.
Tepat ketika mereka memasuki halaman Kedutaan Besar Suriah, Jose melihat seorang laki-laki keluar untuk membuang puntung rokok terakhir yang habis diisapnya.
“Assalamu‘alaikum,” sapa Jose ramah.
Lelaki itu terpaku sejenak, kemudian bertanya, “Anda siapa?”
“Kami dari tim MER-C Indonesia. Saya sendiri seorang dokter dan mereka kawan-kawan saya,” Jose menunjuk beberapa anggota MER-C yang berdiri di belakangnya. Lelaki itu menyimak dengan matanya yang menyelidik, “Saya baru pulang dari Bagdad. Saya keluar lagi karena ingin membeli obat-obatan di negara Anda,” Jose menjawab lugas.
“Oh, silakan, silakan,” sikap lelaki itu melunak dan mengajak mereka masuk ke dalam gedung kedutaan. Lelaki itu menyuguhkan teh khas Timur Tengah sambil berbincang panjang lebar.
“Saudara kita itu ada kekurangannya,” ujar lelaki itu tanpa menyebut nama saudara yang dia maksud, tapi Jose mafhum bahwa yang dimaksudnya adalah Presiden Irak, Saddam Hussein. “Dia punya masalah dengan karakternya,” katanya lagi, seraya tertawa kecil. “Tapi dalam keadaan seperti ini, tidak sepatutnya kita melupakan dia.”
Lelaki itu berpendapat bahwa dalam situasi perang seburuk itu, selayaknya mereka tetap membantu Irak. Selepas percakapan panjang itu, Jose dan kawan-kawan pulang dengan mengantongi visa. Siapa menyangka lelaki yang baik hati itu ternyata Duta Besar Suriah untuk Yordania?!
Maka, sebagaimana pengalaman-pengalamannya berjumpa dengan orang yang ikhlas, di mata Jose, Siti Fadilah adalah seorang pejabat yang tanpa pamrih. Buktinya, tidak ada seorang menteri pun yang masih menjabat berani menentang WHO kecuali Siti Fadilah. Dia bahkan menulis buku Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung.
Buku itu bercerita tentang konspirasi Amerika Serikat dan organisasi Kesehatan dunia, WHO, dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Sebuah buku yang membuat pejabat WHO dan Amerika Serikat terusik. Siti Fadilah menulisnya untuk membela rakyat atas ketidakadilan. Orang-orang seperti itulah, yang biasanya sinkron dengan perjuangan MER-C.
Kini, misi ke Palestina itu menjadi kian niscaya di mata Jose. Tinggal melangkah ke tahap berikutnya; menyiapkan tim. Dia mulai membuat daftar berisikan nama-nama rekan yang kemungkinan siap berangkat saat ini juga.
Jose menghubungi Mursalin, relawan MER-C yang juga Ketua Bidang Kaderisasi Forum Umat Islam. Seperti halnya Jose, dia cukup dekat dengan Menteri Kesehatan dan sering dimintai pendapatnya soal kesehatan dan politik.
“Ya, Ibu Siti tadi juga menghubungi saya,” jawab Mursalin setelah Jose menjelaskan pokok persoalannya.
Jose menjawab, “Kita harus kirim tim. Momennya harus cepat. Bagaimana, kamu siap?”
“Saya, sih, siap saja. Berangkat sekarang kalau bisa juga siap!” jawab Mursalin tegas, meyakinkan.
Mursalin sanggup menyertai Jose untuk berangkat dalam tim yang dibentuk pemerintah. Sedangkan relawan lainnya akan diberangkatkan kemudian, setelah menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan di Gaza.
Tidak seperti biasanya, pasien-pasien membeludak di tempat praktik Sarbini di Jatibening, Bekasi. Dia sedang meredakan penat ketika Jose menelepon. “Kita mau berangkat ke Gaza, nih. Ada serangan Israel. Kamu ikut, ya,” suara Jose terdengar dari balik telepon genggamnya.
Waduh, pasien sedang banyak-banyaknya. Tapi, siap tak siap, Sarbini harus siap. Inilah panggilan jihad yang dinanti-nantinya. Hanya saja, yang Sarbini tak habis pikir adalah setiap kali panggilan misi itu datang, pasiennya selalu saja sedang banyak-banyaknya. Akhirnya dia memandang segi postitifnya saja, bahwa pasien-pasien itu adalah ujian. Ujian berupa pilihan antara uang atau jihad.
Di sisi lain, Sarbini teringat perkataan seorang teman di Mesir, “Kalau Anda pernah minum air Sungai Nil, Anda akan kembali ke Mesir.” Pada saat mengingat kata-kata itu, Sarbini merasa ada benarnya. Sekali dia mengikuti misi kemanusiaan, maka akan ketagihan. Mencandu istilahnya. Apalagi ini Gaza. Bukan main-main jihadnya. Jihad kelas tinggi. Semua manusia beriman pasti mau meraihnya. Maka, pilihannya mantap sudah, dia harus berangkat.
Sementara di Bogor, Faried Thalib sedang menghabiskan akhir pekan bersama istrinya di rumah seorang kerabat. Dia belum begitu memperhatikan ketika berita serangan bom di atas Jalur Gaza itu disiarkan televisi nasional. Seperempat jam kemudian, Jose meneleponnya. “Gaza diserang. Bisa berangkat, nggak?” Pertanyaan Jose singkat namun menembus kalbunya.
“Siap! Saya siap berangkat,” Farid menjawab spontan, tanpa berpikir lagi.
“Berangkat? Berangkat ke mana?” Yuni Wahyudi, istri Faried bertanya penuh curiga. Melihat gelagat suaminya itu, Yuni berusaha keras menebak-nebak apa yang ada dalam pikiran Faried. Yuni dan Faried sudah saling kenal sejak mereka kuliah di Institut Sains dan Teknologi Nasional sehingga Yuni hafal sekali tabiat suaminya itu.
“Uuhmmm …,” Faried menggaruk-garuk kepalanya. Yuni teringat berita tadi pagi soal penyerangan di
Gaza. Pasti mau ke sana!
“Mau ke Gaza?” tanya Yuni penuh selidik.
Faried menarik napas. Dia sudah menduga pertanyaan yang enggan dijawabnya itu. “Boleh, nggak?”
“Dokter Jose ikut?”
“Ikut,” Faried menjawab pendek.
Yuni diam saja. Wanita itu menyadari, melarang tidak ada gunanya. Tekad suaminya sudah bulat. Dulu dia pernah melarang Faried ke Lebanon. Sangat melarang tepatnya. Tapi, toh Faried tetap berangkat. Dan sejak itu dia tak pernah melarang lagi suaminya menjadi relawan dalam setiap misi MER-C.
Di belahan lain Jakarta, berita agresi militer Israel di Gaza membuat Indragiri ternganga di depan televisi. Serangan itu sungguh luar biasa. Hatinya pedih. Seketika batinnya merasakan panggilan yang kuat. Dia tahu, dia akan dipanggil ke Gaza. Istrinya, Tri Handayani, menangis ketika Indra memberi tahu soal firasat itu.
Indra, dokter anestesi kelahiran 22 Januari 1976, termasuk relawan MER-C yang sebelumnya sering berhalangan untuk berangkat menjalankan misi kemanusiaan. Dalam sejarah MER-C, namanya hanya tercatat dalam beberapa misi. Dia hanya mampu menyiapkan peralatan, ikut rembuk, dan melakukan apa saja untuk kebutuhan tim-tim itu. Namun, diam-diam Indra memendam kerinduan untuk berangkat lagi menjadi anggota tim dalam sebuah misi.
Ahad pagi itu, Indra baru saja pulang dari pemakaman seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ketika telepon yang ditunggu akhirnya berdering. Dia memandang layar telepon genggamnya. Dari kantor MER-C. Indra seperti sudah lebih dulu mendengar suara si penelepon sebelum benar-benar mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Dia sudah tahu. Bagi dia, suara di balik telepon itu seperti konfirmasi atas perasaannya sejak melihat berita di televisi semalam.
“Bisa berangkat ke Gaza?” Pertanyaannya singkat saja. “Siap!” Indra menjawab tegas dan lugas. Hubungan telepon dia putus dengan detakan irama jantung yang semakin cepat. Satu tugas berat menantinya di rumah. Meminta izin pada keluarganya. Belum-belum, perutnya sudah mulas.
Sampai di rumah, dugaannya benar. Istrinya hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena larangannya hanya menjadi harapan yang kosong. Indra terdiam, membisu bagaikan patung. Hatinya merintih menyaksikan tangis pilu tersebut. Sungguh, bukannya dia tak peduli, tapi panggilan jihad ini begitu kuat. Panggilan ibadah kepada Allah yang sulit dielakkan. Hatinya sudah mantap. Baginya, panggilan ke Jalur Gaza ini tak ubahnya panggilan dari Tual, sepuluh tahun silam.[]
*Tulisan di atas bersumber dari BAB 1 Buku Jalan Jihad Sang Dokter yang ditulis oleh dr. Joserizal Jurnalis & Rita T. Budiarti